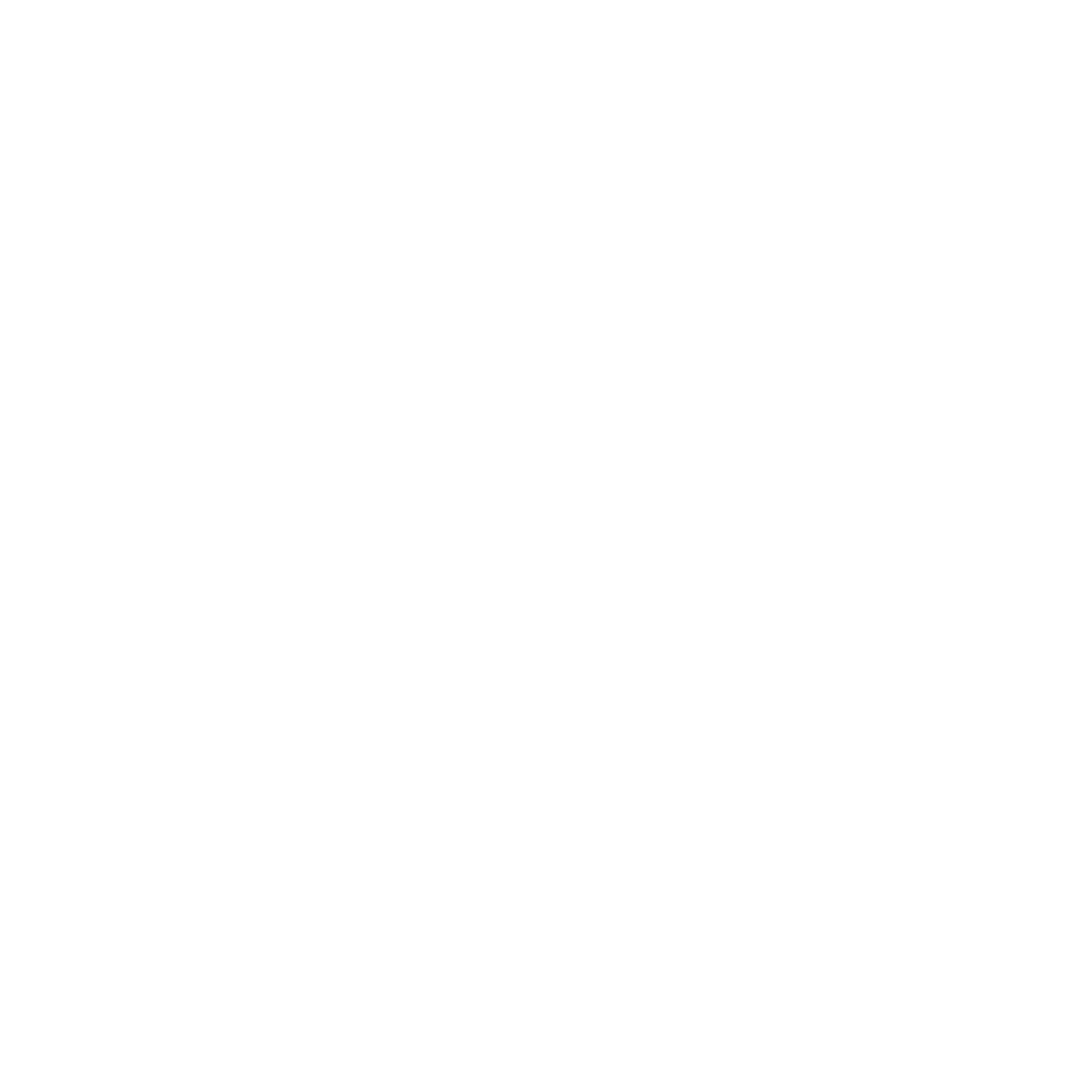Jumat, 14 November 2025 | 8 min read | Andhika R
UU PDP: Antara Cita-Cita Kepatuhan Global dan Ancaman Hukuman bagi Entitas Kurang Mampu
Indonesia telah memasuki era baru tata kelola data dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini merupakan tonggak historis yang secara ambisius menempatkan perlindungan data pribadi sebagai hak fundamental, sejalan dengan standar global seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Euforia atas hadirnya payung hukum ini di satu sisi memberikan harapan besar bagi jaminan privasi warga negara. Namun, di sisi lain, muncul sebuah pertanyaan filosofis sekaligus pragmatis yang menggantung di udara: Mampukah UU PDP benar-benar memantik kepatuhan kolektif dan mendorong ekosistem digital yang sehat, atau justru berpotensi merangkul standar penegakan hukum yang lebih mudah menyasar pihak yang kurang mampu secara finansial dan struktural?
Argumen sentral dalam tulisan ini adalah bahwa implementasi UU PDP di Indonesia—khususnya pada fase transisi dan penegakan—menghadapi risiko signifikan berupa kesenjangan kepatuhan. Kesenjangan ini tercipta oleh disparitas sumber daya, literasi, dan kompleksitas regulasi antara Big Tech atau korporasi besar yang masif memproses data, dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional. Apabila penegakan hukum dan sanksi yang diatur dalam UU PDP tidak diimplementasikan dengan strategi yang diferensiasi dan inklusif, regulasi yang seharusnya menjadi perisai bagi hak privasi justru bisa berubah menjadi pedang yang menghambat inovasi dan menumbangkan pelaku usaha kecil.
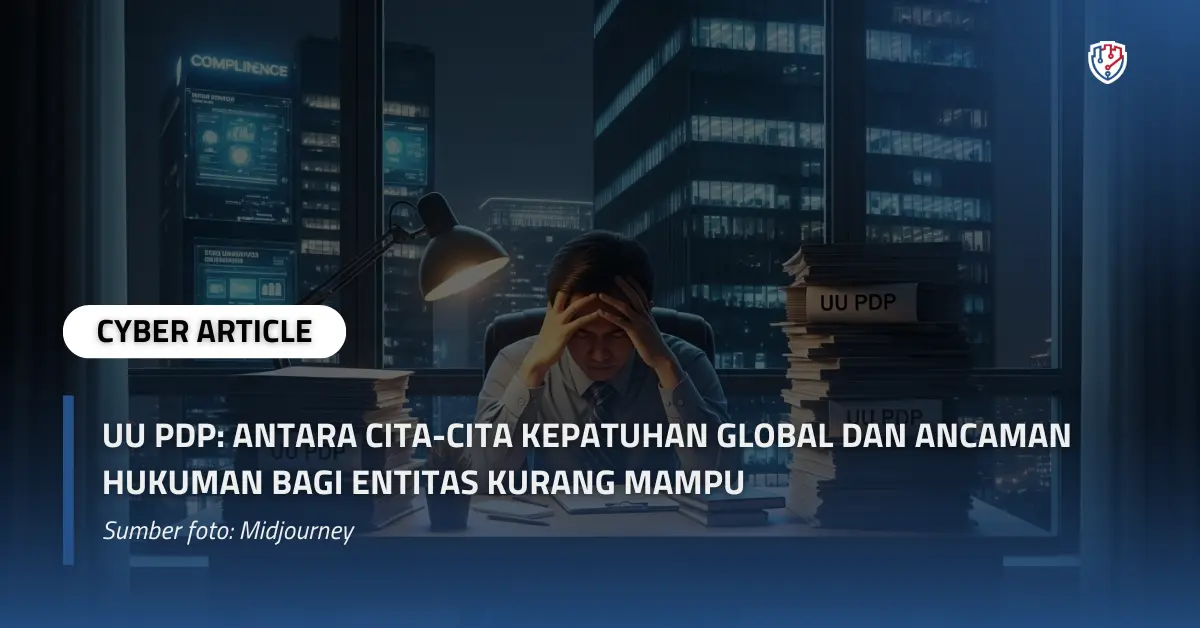
I. Anatomi Kekuatan UU PDP: Standar Global dan ‘Gigi’ Sanksi
UU PDP hadir mengisi kekosongan hukum yang selama ini hanya mengandalkan regulasi sektoral yang tersebar dan tidak terintegrasi. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip universal, UU ini menetapkan kerangka hukum yang kokoh.
A. Prinsip Fundamentalisme Data Pribadi
UU PDP memperkuat hak subjek data—individu pemilik data—seperti hak untuk mengakses, mengoreksi, menghapus, hingga menarik persetujuan atas pemrosesan data mereka. Prinsip-prinsip pemrosesan data, mulai dari legalitas, proporsionalitas, hingga akuntabilitas, menjadi kewajiban mutlak bagi Pengendali Data Pribadi (PDP) dan Prosesor Data Pribadi (PrDP). Tuntutan transparansi ini menuntut perubahan total pada model bisnis yang selama ini terbiasa mengumpulkan data secara masif tanpa persetujuan eksplisit.
B. Arsitektur Sanksi: Ancaman Finansial dan Pidana
Kekuatan normatif UU PDP terletak pada rezim sanksi yang bersifat berlapis dan berat. Sanksi ini dibagi menjadi tiga kategori utama:
- Sanksi Administratif: Berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, hingga denda administratif maksimal 2% dari pendapatan tahunan korporasi. Denda yang progresif ini ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh entitas yang kaya sumber daya.
- Sanksi Pidana: Dikenakan pada pelanggaran berat dengan unsur kesengajaan, seperti pemalsuan data, perolehan ilegal, atau pengungkapan data yang bukan miliknya. Ancaman hukuman pidana penjara dapat mencapai 6 tahun dan denda maksimal Rp6 miliar untuk individu, serta pidana tambahan berupa pembubaran korporasi.
Perbandingan dengan regulasi global menggarisbawahi urgensi sanksi ini. GDPR, misalnya, menerapkan denda hingga €20 juta atau 4% dari total omzet global tahunan. Meskipun secara nominal sanksi UU PDP terlihat lebih rendah, bagi konteks ekonomi Indonesia, denda 2% dari pendapatan tahunan sudah merupakan ancaman eksistensial bagi banyak perusahaan, kecuali bagi segelintir korporasi teknologi raksasa.
II. Kesenjangan Kapasitas: Realitas di Garis Depan Implementasi
Meskipun fondasi hukum UU PDP terlihat ideal, realitas implementasinya dihadapkan pada tantangan yang tidak seragam. Isu utama adalah disparitas sumber daya yang menciptakan kesenjangan kepatuhan antara Big Tech dan UMKM digital.
A. Mahalnya Ongkos Kepatuhan Struktural
Kepatuhan terhadap UU PDP bukan hanya sebatas membuat privacy policy baru; ia menuntut investasi substansial dalam tiga aspek utama:
- Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keahlian: UU PDP mengamanatkan penunjukan Petugas Perlindungan Data atau Data Protection Officer (DPO), terutama bagi entitas yang memproses data dalam skala besar atau data spesifik. Di Indonesia, talenta DPO yang tersertifikasi masih terbatas. Bagi korporasi besar, ini adalah operational expenditure yang terukur. Namun, bagi UMKM atau startup kecil, biaya merekrut atau menyewa jasa DPO eksternal (DPO as a Service) bisa menjadi penghalang finansial yang masif.
- Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Siber: Kewajiban untuk menjamin keamanan data pribadi subjek data menuntut implementasi teknologi keamanan tingkat lanjut (enkripsi, penetration testing, data loss prevention). Banyak UMKM masih mengandalkan sistem lama atau solusi gratis yang rentan. Investasi untuk mencapai standar keamanan yang memadai, termasuk sertifikasi internasional seperti ISO 27001 dan ISO 27701, membutuhkan puluhan hingga ratusan juta rupiah—sebuah angka yang mustahil dipenuhi oleh bisnis mikro.
- Audit dan Tata Kelola Hukum: Proses pemetaan data (data mapping), penilaian dampak privasi (DPIA), dan penyelarasan kontrak dengan PrDP adalah proses hukum dan teknis yang rumit, membutuhkan konsultan hukum spesialis. Keterbatasan literasi digital dan hukum di kalangan pelaku UMKM memperburuk kondisi ini.
B. Risiko Compliance Burden pada UMKM
Data menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami regulasi ini. Jika penegakan dilakukan secara seragam, mereka yang paling rentan dihukum adalah pihak-pihak yang:
- Melakukan Pelanggaran Non-Sengaja: Kelalaian sederhana dalam pengelolaan customer relationship management (CRM) atau berbagi data mailing list dengan mitra tanpa persetujuan eksplisit.
- Tidak Mampu Melakukan Mitigasi: Tidak memiliki tim hukum yang mampu menangkis gugatan atau negosiasi sanksi.
Akibatnya, sanksi UU PDP yang seharusnya menghukum perilaku eksploitasi data masif, justru berpotensi menjadi "pajak" bagi ketidakmampuan struktural entitas kecil dalam memenuhi birokrasi dan standar teknis yang idealistik. Hal ini bertolak belakang dengan semangat UU PDP yang seharusnya melindungi semua pihak, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.
III. Polemik Kelembagaan dan Potensi Konflik Kepentingan
Kunci efektivitas UU PDP ada pada Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi. Pasal 58 UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Model ini secara fundamental berbeda dari model komisi independen (independent data protection authority) yang dianut oleh GDPR.
A. Debat Independensi Lembaga Pengawas
Banyak kajian akademis menyoroti bahwa peletakan Lembaga Pengawas di bawah ranah eksekutif berpotensi menimbulkan conflict of interest, terutama ketika kasus pelanggaran melibatkan badan publik atau instansi pemerintah. Sebagai regulator, Lembaga Pengawas seharusnya memiliki kewenangan quasi-judicial dan independensi penuh untuk memastikan keputusannya didasarkan murni pada penegakan hukum, bebas dari intervensi politik atau kepentingan sektoral.
Ketidakjelasan struktur dan wewenang lembaga ini selama masa transisi telah menciptakan ketidakpastian hukum. Tanpa lembaga yang kuat dan independen, mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi maupun ajudikasi administratif, tidak dapat berjalan optimal. Ini secara langsung melemahkan kemampuan UU PDP untuk mengejar pelanggaran besar yang dilakukan oleh pemain-pemain utama dalam data.
B. Ancaman Sanksi Pidana: Siapa yang Diutamakan?
UU PDP membagi sanksi pelanggaran menjadi administratif dan pidana. Sanksi pidana diarahkan pada tindakan yang melawan hukum seperti pengungkapan, penggunaan, atau perolehan data pribadi secara ilegal dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.
Pertanyaannya, apakah penegak hukum akan memprioritaskan kasus data breach oleh korporasi yang merugikan jutaan subjek data, atau kasus kecil yang melibatkan oknum individu? Jika penegakan pidana lebih sering menyasar kasus-kasus low-profile yang mudah diselesaikan, sementara kasus-kasus besar (yang melibatkan Big Tech) diselesaikan dengan denda administratif yang dianggap sebagai cost of doing business, maka tujuan pencegahan UU PDP akan gagal. Hukum harus dipastikan efektif menghukum entitas yang melakukan eksploitasi data secara sistematis dan merugikan publik secara luas.
IV. Membangun Kepatuhan yang Inklusif: Sebuah Investasi Kepercayaan
Untuk menggeser narasi dari sekadar "UU Hukuman" menjadi "UU Kepatuhan", strategi implementasi harus berfokus pada inklusivitas dan edukasi.
A. Strategi Tiered Compliance dan RegTech
Pemerintah perlu menerapkan strategi kepatuhan UU PDP yang bertingkat (tiered compliance), di mana standar teknis dan kewajiban DPO disesuaikan dengan skala dan jenis data yang diproses oleh entitas.
- UMKM: Diberikan panduan compliance yang disederhanakan, checklist berbasis risiko rendah, dan grace period yang lebih panjang.
- Solusi Regulatory Technology (RegTech): Mendorong pengembangan solusi RegTech lokal yang terjangkau bagi UMKM, yang mampu mengotomatisasi pemetaan data dan permintaan hak subjek data, sehingga biaya kepatuhan dapat ditekan serendah mungkin.
B. Mengarusutamakan Literasi Data Pribadi
Tantangan implementasi UU PDP yang paling mendasar adalah rendahnya literasi digital dan kesadaran privasi. Kampanye edukasi harus diarahkan tidak hanya kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada masyarakat sebagai subjek data, agar mereka proaktif menggunakan hak subjek data mereka.
Ketika subjek data menjadi lebih berdaya (misalnya, berani mengajukan keberatan atau permintaan penghapusan data), ini secara alami akan mendorong Pengendali Data Pribadi untuk patuh, terlepas dari ukuran organisasinya. Kepatuhan tidak datang dari rasa takut terhadap sanksi, tetapi dari pemahaman bahwa data adalah aset yang wajib dilindungi.
Penutup: Menjaga Keseimbangan Demi Kedaulatan Data
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan cermin ambisi Indonesia dalam membangun ekosistem digital yang berdaulat dan beretika. Ia adalah sebuah harapan—sebuah blueprint kedaulatan digital. Namun, hukum hanyalah sehelai kertas jika penegakannya timpang.
Masa depan UU PDP akan ditentukan oleh keseimbangan yang tercipta: apakah Lembaga Pengawas yang baru mampu mengontrol kekuatan data raksasa dan memaksakan akuntabilitas melalui sanksi berat (administratif dan pidana) yang proporsional, atau justru terjebak dalam perangkap birokrasi yang lebih mudah menghukum entitas kecil yang kekurangan kapasitas.
Jalan menuju kepatuhan kolektif yang sejati mengharuskan pemerintah untuk tidak hanya fokus pada ketajaman sanksi, tetapi juga pada infrastruktur edukasi dan model penegakan yang berempati terhadap realitas ekonomi. Hanya dengan pendekatan yang diferensiasi dan inklusif, UU PDP dapat berfungsi sebagai landasan perlindungan data yang kuat, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat digital Indonesia.
Andhika RDigital Marketing at Fourtrezz
Artikel Terpopuler
Tags: Penetration Testing, Keamanan Siber, Audit IT, Resiliensi Siber, Fourtrezz Pentest
Baca SelengkapnyaBerita Teratas
Berlangganan Newsletter FOURTREZZ
Jadilah yang pertama tahu mengenai artikel baru, produk, event, dan promosi.